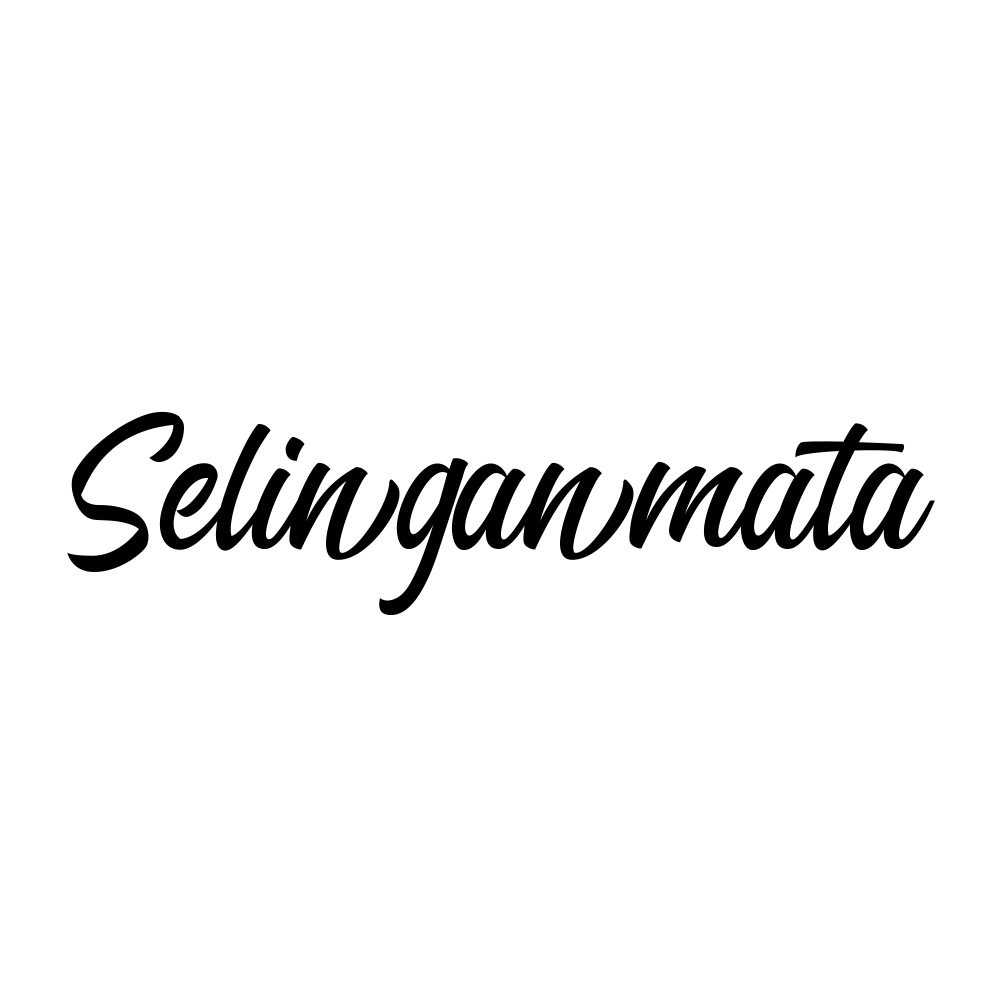Seperti biasa, udara di Pandaan memaksa saya mengenakan jaket hanya untuk sekadar menahan udara dingin dan badan tetap terasa hangat.
Waktu menunjukkan pukul 21.12 wib, cuaca malam sangat cerah, bulan dan bintang di langit berdampingan cukup mesra membuat kesan tersendiri bagi saya, di hari-hari terakhir berada di tanah kelahiran.
“Mlaku-mlaku kono lho, jak en Raziq nang pasar malem ndek Jasem kono (jalan-jalan sana, ajak Raziq ke pasar malem di Jasem situ)” celetuk Neng Wa.
Nama lengkapnya Ma’rifah, tapi saya biasa memanggilnya Neng Wa, adik kandung paling bungsu dari almarhumah Ibu saya.
Perawakannya langsing, tinggi, murah senyum, sampai-sampai semua tukang Bakso disenyumin. Ya, hampir tiap hari dia memilih bakso sebagai menu makan siangnya. Kadang juga mie ayam pangsit sebagai variasi.
Dulu waktu saya kecil, Neng Wa lah yang antar jemput saya ke sekolah. Kala itu masih duduk di TK Dharma Wanita. Sudah tenggelam bersama lumpur lapindo segala kenangannya.
“Sidoe moleh kapan le?” tanya Cak Mael, suami dari Neng Wa.
Di hari-hari terakhir saya di Jawa, pertanyaan serupa banyak saya terima. Sedih sebenarnya. Bukan! bukan karena seakan mereka mengusir dengan pertanyaan itu, hanya saja dapat diartikan bahwa waktu kepulangan saya kembali ke tanah rantau sudah semakin dekat.
“Sik dereng pasti cak Mael.” saya menjawab sekenanya.
Malam semakin larut, saya mengambil motor. Tampak dikasur kamar bagian depan adik sepupuku rebahan sembari bermain gawai. Sembari merapikan jaket, saya menegurnya.
“Yuk, nang pasar malem” saya mengajaknya.
Sosok tinggi besar itu bangkit dari tempat tidur. Merapikan baju, dengan cepat ia bergerak ke teras rumah. Tanpa basa basi kami berangkat ke pasar malam yang jaraknya tidak sampai lima menit dari rumah.
*
Muhamad Rusdi Hanif, a.k.a Hamik, Hambrol, atau MRH. Entahlah, banyak julukannya. Anak pertama dari Neng Wa dan Cak Mael. Sekarang sedang mengabdikan diri di salah satu kampus peradaban di Sidoarjo. Anak kuliahan katanya. Maba; MAhasiswa Barusan Aja.
Jika masa kecil saya diantar jemput oleh Neng Wa, sama halnya dengan Hanif. Sejak kecil ia dirawat sama Almarhumah Ibu saya, karena Neng Wa bekerja.
“Ga ngerti sampe kapan, Cuma sing gawe acara iki arek-arek Karang Taruna,” kata Hanif sesaat setelah parkir motor.
Kami berjalan menyusuri lorong keramaian masyarakat. Ada yang menawarkan mainan, ada yang jualan kuliner lokal, ada juga yang hanya sekadar berjalan menghilangkan kepenatan.
“Papa, papa Aziq mau pancing-pancing itan (baca: Ikan),”
Raziq yang sedari tadi antusias melihat banyaknya pilihan mainan akhirnya memilih memancing ikan mainan sebagai pembuka ceritanya di pasar malam Jasem. Bermodal Rp5000 Raziq akhirnya memancing ikan yang berenang tanpa air.
“Atos anying sosise!” celetuk Hanif saat menggigit sosis bakar yang saya beli.
Alunan musik dangdut yang cukup keras seakan mengajak untuk segera bergoyang. Di ujung sana seseorang berteriak diatas panggung, terdengar sayup seperti sedang mengumumkan pemenang lomba. Entah apa yang telah mereka lombakan. Mungkin makan krupuk sambil jongkok.
Saya masih menikmati sosis yang bertekstur keras. Hanif sibuk mengasah skill fotografinya, dengan mengabadikan setiap momen yang masuk dalam lingkaran pandangan matanya.
Raziq? Ia berusaha mengukir ceritanya sendiri, cerita bermain di sebuah pusat keramaian tradisional yang mungkin akan sulit ia temukan di Gorontalo.
Tanpa saya sadari Raziq sudah berpindah tempat bermain. Setelah bosan memancing, Ia memilih playground untuk menyalurkan hasrat bermainnya. Tak lama kemudian, Ia melanjutkan dengan permainan tembak menembak.
Bosan pun tiba, rasa lapar membawanya meninggalkan segala keramaian di pasar malam Jasem. Kami bertiga memutuskan melanjutkan penghabisan malam itu ke pusat Kota Pandaan.
“Bapak titip tuku sego goreng,” ujar Hanif sembari fokus membawa motor.
Malam semakin dingin. Ditengah jalanan yang sunyi, kami melenggang menuju minimarket untuk membeli camilan, kemudian menikmatinya. Bercengkerama bertiga, seakan lupa bahwa waktu berpisah akan segera tiba.
Kedekatan saya dengan Hanif memang tak ubahnya Kakak dan Adik. Sikapnya yang cuek dan “asal njeplak” terkadang membuat orang yang baru mengenalnya akan tersulut emosi.
“Kak, ojo lali mampir sego gorenge Bapak,” Hanif kembali mengingatkan.
Waktu menunjukkan pukul 00.35 wib, artinya hari sudah berganti dan malam semakin larut. Kami kembali menyusuri jalanan Kota Pandaan yang semakin lengang menuju lokasi warung nasi goreng, melihat kiri kanan bahu jalan warung kopi lesehan berjejeran. Bahkan ada yang berjualan dipelataran kuburan. Menyeramkan bukan?
“Nasi Goreng Jakarta mas dua bungkus,” saya memesan kepada penjual nasi goreng.
Sembari menunggu pesanan selesai saya memandangi langit gelap yang masih memamerkan kemesraan bulan dan bintang, sembari menghayal entah kapan bisa kembali memandangi langit malam Kota Pandaan.
Raziq sibuk sendiri, saking asyiknya piring kecil berisi cabai ia tumpahkan. Saya dan Hanif pura-pura tidak tahu.
“Ini mas. Totalnya Rp18 ribu,” ujar si penjual nasi goreng.
Sesampainya dirumah, nasi goreng menjadi pemersatu. Duduk melantai didepan kamar, menikmati setiap suapan. Cak Mael, saya dan Hanif larut dalam bungkusan nasi goreng. Perut yang sedari tadi keroncongan, seketika diam dan sunyi.
Baju terasa ketat, mata mulai sayu mungkin saja karena tiupan angin malam dan rasa kenyang. Raziq? Dia sibuk menggoreskan ceritanya sendiri diatas bantal.